KEJARLAH KEINDAHAN
Kala itu,
begitu tebal kabut embun menyelimuti pagi. Sinar mentari yang menghangatkan tiap
tubuh manusia dari kebekuan dinginya malam, tak sampai menyentuh hamparan
permukaan bumi tempat mereka berpijak. Di atas pepohohanan, depan ndalem
Abah Amin, terdengar kicauan burung-burung yang bersahutan dengan suaranya yang
nyaring dan merdu, mengalunkan melodi harmoni alam menyambut pagi, mengiringi hembusan
angin yang masih begitu segar, menyapa penduduk pedesaan dan perkampungan.
Di atas lantai
teras ndalem Abah Amin, Fatan, pandangnya menerawang jauh, menerbangkan
angan, terduduk menunggu kedatangan beliau. Ia tahu, bahwa beliau belumlah
kembali dari Masjid seusai mengimami para jamaah sholat Shubuh. Ruang tamu
masih terlihat begitu sepi. Lampu neon 40 watt yang begitu terang memancarkan
cahanya ke setiap sudut ruangan, masih belum dinyalakan, untuk sekedar menunggu
datangnya matahari bersinar terang menggantikan.
<a href="signin.php" rel="nofollow">sign in</a>
<a href="signin.php" rel="nofollow">sign in</a>
Rumah
tempat Abah Amin bersama keluarganya memang tergolong biasa dan sangat
sederhana. Ada ruang tamu, beberapa kamar; satu untuk beliau dan istrinya, dua
untuk kedua anaknya, dan satu lagi untuk para tamu yang datang menginap. Di
tengah-tengahnya ruang makan. Dan di belakang sendiri ruang dapur. Biarpun
sudah berdiding tembok, kombinasi kayu sebagai perpaduan masih terlihat begitu
kentara. Smakin menambah kesederhanaan beliau dalam hidup.
Di rumah
itulah biasanya Fatan tiap pagi membuka pintu dan jendelanya. Kotoran-kotoran
ia bersihkan dari lantai. Ia tahu tamu Abah Amin tergolong tidak sedikit.
Kebersihan harus dijaga untuk memberi rasa nyaman para tamu yang datang. Ia
lakukan itu dengan penuh keihklasan demi kenyamanan orang lain. Tak apalah
letih sedikit setiap pagi. Apalah krugianya jika dibanding dengan kenyamanan
para tamu.
“Fatan,
tamu dalam agama kita diibaratkan seperti raja. Maka harus kita mulyakan”.
Begitu pesan beliau padanya kali pertama dia tinggal di pesantren sebagai santridalem. Pesan itu begitu diingatnya betul-betul untuk dipraktikkan dalam
sehari-hari. Aturan dalam Islam itulah yang membuat dirinya sangat ikhlas. Dari
aturan itu pula, ia paham bahwa agamanya sangat toleran terhadap orang lain.
Siapa pun mereka, apabila bertamu di rumah kita, penghormatan harus selalu
dijaga biar mereka merasa nyaman.
Selain
itu, Fatan juga tahu, bahwa kebersihan adalah sebagaian dari iman. Allah juga
memberi pengakuan dalam firmanya, bahwa Dia Maha bersih dan mencintai
kebersihan. Sebagai hambaNya yang taat, Fatan mencoba terus mempraktikan
prilaku yang diajarkan olehNya dalam Islam.
Setiap
kotoran yang ada dilantai ia sampu bersih. Asbak yang penuh dengan puntung
rokok dan abunya ia buang ke tempat sampah yang disediakan di halaman belakang
rumah. Apabila tempat sampah itu menumpuk, ia membakarnya. Sisa pembakaran itu
dikumpulkanya unntuk dijadikan pupuk. Di halam depan rumah Abah Amin memang
banyak bertumbuh hiasan-hiasan bunga. Ada yang di pot, ada yang langsung
ditanam di tanah.
Selesai
membersihkan ndalem, ia lanjutkan menyapu halaman depannya lalu menyirami pohon
dan bunga-bunga disekitarnya. Ia lakukan itu agar tanaman mendapatkan air untuk
tumbuh. Selai itu akan menambah keindahanya ketika dipandang oleh kita. Karena
tanaman yang sering disirami air, akan tampak selalu segar.
“Ibarat
tanaman, hati kita akan terus segar jika disirami oleh air kesejukan dari pesan
Al Qur’an dan Sabda-sabda Nabi.” Begitu pesan beliau pada suatu pengajian rutin
di pesantren. Ia pahami betul-betul apa yang diucapkan sang Kiai kepadanya dan
santri-santri lainya. Bukan hanya untuk sebagai bahan pengetahuan otak, tapi
pesan itu terus ia coba praktikkan. Setiap orang bisa mengetahui tentang Islam,
tapi belum tentu mereka praktikkan. Praktik sungguh sangat sulit dari pada sekedar
mencari pengetahuan.
Tapi, tidak
untuk pagi ini. Fatan pagi-pagi setelah sholat Shubuh langsung berkemas-kemas.
Barang yang akan dibawanya dipersiapkan semua. Selesai berkemas-kemas, fatan
langsung menuju Ndalem Abah Amin. Sesampai di depan Ndalem, ia melihat
masih sepi. Ia pun duduk dilantai menunggu kedatangan Abah Amin. Walaupun ia
tahu, sebenarnya Umi Khafsoh, istri Abah Amin, ada di ndalem.
Pagi itu
ia tahu, bahwa Istri beliau berjama’ah Shubuh di Musholla belakang bersama
santri-santri putri. Biasanya Umi Khafsoh berjama’ah di Masjid. Tapi entah,
ketika itu ia melihat berjamaah di Mushola belakang. Santri seniorlah yang
biasa mengimami Sholat Shubuh secara bergantian dengan jadwalnya masing-masing.
Ini dimaksudkan oleh Kiai agar mereka terbiasa sewaktu telah pulang ke rumah
masing-masing. “Santri harus siap apabila masyarakat membutuhkan kita. Paling
tidak kita siap apabila dituntut untuk menjadi imam sholat.” Begitu pesan Abah
Amin pada suatu pengajia rutinnya. Meski begitu, aku tetap harus menunggu Abah.
Niatku
kini sudah bulat untuk meninggalkan pondok pesantren. Aku tak peduli, walau
nanati Abah Amin melarangku. Semuanya sudah kupersiapkan dengan penuh
pertimbangan yang masak. Ini pilihanku. Aku sadar pilihan ini ada resikonya.
Biarlah resiko itu kutanggung sendiri. Karena setiap manusia punya pilihan
masing-masing dan harus bertanggung jawab pada pilihanya tersebut. Kita bebas
bebuat sekehendak hati, tapi ingat bahwa kehendak kita harus kita
tanggungjawabi. Apabila kehendak kita melanggar aturan, maka kita harus siap
dihukum. Begitu piker Fatan.
Tak lama kemudian, Abah Amin datang. Aku pun langsung berdiri menyambutnya dengan ucapan salam. Lalu
kucium tangan beliau, sebagai penghormatan beliau orang yang lebih
berpengatahuan agama dan mau mengajarkanya pada orang lain sebagai pengabdian.
Belum juga kulepas tanganya dari tanganku, beliau sudah bertanya.
“Fatan, apa
kamu nggak sholat?”.
“Sudah,
Bah. Tadi di kamar, sholat sendiri.”
“Tidak
ikut berjama’ah kenapa, Fatan?”
“Tidak,
Bah.”
“Kenapa?
Apa kamu ada masalah?”
“Tidak
Bah!”
“Terus
ini, mengapa tiba-tiba menungguku di teras pagi-pagi buta?”
Mendengar
pertanyaan Fatan, hanya bisa terdiam. Harus dimulai dari mana aku meminta izin.
Ia bingung. Kebaikannya selama ini begitu membayang dibenaknya. Sampai ia
kebingungan untuk izin pergi. Meski entah akan kembali atau tidak. Dengan
kepala tertunduk, ia pun memaksa diri untuk menjawabnya. Namun tetap saja,
jawaban itu seperti tertahan dikerongkongan. Masih dia tundukan kepala di depan
beliau. Fatan merasa tak berani hanya sekedar memandang wajah keteduhan Abah
Amin. Pancaran air mukanya yang begitu bersinar, tentu akan membuat setiap
orang merasa sungkan bila memandangnya secara langsung.
“Ya sudah!
Mari masuk dulu!”
“Maaf, bah! Disini saja Bah, Saya hanya ingin pamit.”
“Pamit? ”
“Iya bah, saya mau pamit !”
“Kamu mau pamit kemana? Kamu nggak betah di sini? ”
“Bukan Bah,
bukannya saya tidak betah tinggal disini, Bah. Bukan itu masalahnya.”
Mendengar pertanyaan itu, Fatan kembali terdiam, tertunduk. Ia bingung
harus menjawab bagaimana. Ia sendiri belum jelas apa masalah yang dirasakanya
sekrang. Ia hanya merasa hatinya menuntunya untuk pergi mencari sesuatu yang
tidak ia temukan di pesantren. Sepertinya, ia tinggal dua tahun lebih, rasa
hati yang menggelisahkan itu belum terobati.
“Lalu masalah apa ? ” beliau tanya kembali dengan suara yang
begitu santun dan penuh penghargaan pada setiap orang lain. Tak pedulia ia
santrinya sendiri.
“Maaf bah, saya tak bisa mengatakanya”
Mendengar
jawaban itu, Abah Amin pun terdiam. Tak lama kemudian beliau mengatakan.
“Hemm..
Abah bisa mengerti. Sedikit banyak Abah telah mengamati keberadaan kamu selama
di Pesantren ini, Tan. Memang terkadang hidup yang kita anggap menyenangkan, itu justru berbeda setelah
kita alami. Abah bisa mengerti jalan pikiran dan perasaanmu sekarang. Kamu
belum bisa menerima semua ini, bukan?. Entah kamu
sadari atau tidak, Fatan. Terkadang hidup ini memang tidak
adil apabila kita rasakan. Tapi, ketidakadilan itu justru akan membuat kita
nyaman jika ketidakadilan yang kita anggap itu kita warnai dengan keindahan. Ada
hikmah yang disembunyikan oleh Allah untuk kita pehami. Apabila niatmu sudah
bulat, Abah tidak bisa memaksamu
untuk tinggal disini. Pergilah, tan. Kejarlah keindahan yang kau cari selama
ini. Aku mengizikanmu untuk pergi. Hati-hatilah nanti bila diperjalanan!”
Mendengar
itu, Fatan hanya bisa tertunduk diam. Kata-kata yang beliau ucapkan kepadanya,
membuatnya tak berkutik. Ia tak mampu menjawab atau sekedar merespon dengan
ucapan. Sungguh berwibawa dan dalam pengetahuan beliau, sampai ia tak memahami
isi maksud yang diucapkannya pada dirinya. Apa yang dimaksud dengan keindahan,
ia tak mengerti. Yang ia tahu, hatinya menuntutnya untuk pergi mencari sesuatu
yang bisa memberi kepuasan batin. Ia benar-benar bingung atas penyataan Abah
Amin itu. Yang jelas ia telah diberi izin. Untuk inilah ia menunggu beliau.
Karena itu, ia langsung pamit untuk pergi.
“Terima
kasih atas izinnya, Bah. Bah, Fatan mohon Ridho dan do’anya.” Ucap Fatan dengan
nada lirih. Nada kesedihan ia tahan. Hatinya terasa ingin menangis meninggalkan
orang yang begitu baik, santun, dan penuh pengertian.
“Semoga
Allah meridhoi kamu, Tan. Abah juga ikhlas engkau pergi. Do’a Abah akan selalu
bersamamu. Hanya ingatlah, setelah kamu mendapatkan keindahan pada dirimu, aku
berharap padamu untuk kembalilah ke sini. Kau harus kembali, Tan. Itu pesan
Abah.”
“Ya Bah,
Fatan akan selalu mengungat.”
“Ya
sudah, hati-hatilah dijalan!”
Kucium
kembali tangan beliau dengan penuh kesedihan yang mengharu. Setelah itu ia
langsung pergi.
“Assalamualaikum,
Bah”
“Waalikumsalam….”.
Dengan
perasaan yang tak menentu, hati merasa ingin menangis, ia langkahkan kakinya
berjalan menjauhi Abah Amin yang masih berdiri ditempat. Selamat tinggal, bah.
Selamat tinggal kawan-kawan. Rintihnya dalam hati.
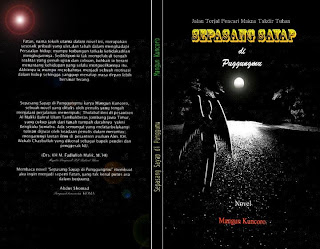
Komentar
Posting Komentar