Lebaranku Antara Jawa-Sumatra
Magrib
ini akan menjadi pamungkas dari segala cerita: indahnya bulan yang suci,
menyimpan berjuta berkah, melipat gandakan segala tingkah dan perbuatan. Perlahan
akan berlalu. Tinggal menunggu detik aja selepas magrib; pengumuman dari
Menteri Agama, semuanya akan tergantikan sorakan kemenangan.
Ada yang beda memang. Jika
sewaktu kecilku dulu, hari kemenangan telah disambut ba’da adzan maghrib.
Sekarang tak lagi begitu. Cecok tentang penentuan hari kemenagan menjadi warna
di negeriku. Ada yang duluan, ada yang terakhir atau apalah. Aku juga tak
terlalu banyak mengerti tentang itu. Mana yang benar dan yang salahpun
masih samar. Tapi biarlah keyakinan
masing-masing kita yang membenarkan. Karena hanya itu jawaban tertinggi.
Keyakinan.
<a href="signin.php" rel="nofollow">sign in</a>
“ Allahu Akbar....Allahu
Akbar...Allahu Akbar...” hu, suara ustad Faqih mulai berkumandang. Dari
ketinggian menara masjid Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas. Penentu bagi
kami; santri dan masyarakat sekitar pesantren. Jika ustad Faqih telah
berkumandang berarti pemerintah telah mengambil keputusan malam ini. Kemudian
disusullah alunan pemujaan dari mushola dan masjid sekitar. Riuh terdengarnnya.
Lantunan takbir yang nyaring. Menggugah jiwa, merekahkan bibir untuk mengikuti
pujian terindah sepanjang masa itu.
“ Allahu Akbar...” bibirku pun
mulai melafalkan pujian itu. Terduduk manis di sudut kamar pondokku. Menjepit
sebatang rokok yang terselip diantara jari tengah-telunjuk. Membumbungkan segala
riuh di jiwaku pulah. Ah, rasanya buru kemarin aku menjalankan puasa. Tak terasa
satu bulan terlalui, Alhamdulillah Ya Robb. nikmatMu teramat besar untuk
sekedar kupungkiri.
***
“ Andi, ayo berangket. Teman-teman
la nunggu galo.”
“ Iyo, ..kelak dulu.”
“ Ah lamo nian.”
“ Bapak, Andi berangkek takbir
keliling kek temen-teman.” Ku sabet obor minyak tanah yang telah kupersiapkan
sejak siang tadi. Berlari tanpa perlu mendengar jawaban bapak.” Ayolah.” Ajakku
beralih.
Ini surau kami. Jaraknya tak
begitu jauh dari rumahku. Disini biasanya kami ngaji TPA bersama ustad Umar.
Bermain bersama teman-teman mengahabiskan sore. Surau ini telah mengukir beribu
kisah tentangku: susahnya belajar alif, ba’ hingga iseng jail teman-teman mengejekku
dengan seorang gadis seberang rumah. Apalagi bulan ramadhan: hapir satu hari
penuh aku dan teman-temanku berada di surau. Serunya pesantren kilat yang
dibimbing ustad Umar mengajari betapa indahnya bulan penuh berkah itu.
Dan malam ini. Surau ini akan
menjadi saksi kembali dalam kisahku. Malam ini awal kali aku mengakhiri puasaku
sebulan penuh. Tanpa cacat sedikitpun. Dan inilah awal aku mendendangkan takbir
kemenangan yang sesungguhnya. Hah, kisah ini takkan pernah terlupakan olehku.
Kisah dimana aku mulai mengerti menyambut hari kemenangan. Kisah yang bukan
hanya sebuah tradisi tahunan yang tak berkesan. Namun, sesungguhnya nikmat
Allah karena telah melakukan perintahnya dengan segala kerendahan hati.
“ Allahu Akbar... Allahu
Akbar...Allahhu akbar...” Di perempatan jalan penghubung kampungku terdengar
gemuruh pujian itu. Suara bersahutan memecah keheningan malam. Menuntun
penghuni langit untuk ikut tertatih melafalkan. Lagit seakan menghilangkan
kengeriannya, awan hitam menggumpal tak tampak sedikitpun.
Itu mungkin gerombolan Roni, TPA
kampung sebelah, temanku SD pula. Ternyata mereka dah mulai keliling. Wah seru
nampaknya.
“ Ustad Umar, ayo berangkek. TPA
kampung sebelah la terdengar tu.”
“ Iyo, galonyo baris yang rapi,
idak boleh nakal, idak boleh belogo. Yok. Kito sambut kemenangan, Allahu
Akbar...” ustad Umar nampak bersemangat. Hem, ustad Umarkan juga mesih muda.
Berisitripun belum.
Malam semakin larut, lantunan
takbir semakin memecah keheningan. Aku bertemu gerombolan Roni, dan kamipun
berpadu setalah sampai di penghujung jalan kampung. Tak ada secuilpun rasa gundah
di raut kami. Rebana, beduk, sulut obor, mewarnai kegembiraan. Sumuannya nampak
girang malah. Huh, sungguh indah suasana malam ini. Mungkin berto-ton emaspun
tak mampu menebusnya.
***
Subuh menyambut, denting takbir
turus berkumandang semalaman. Toa masjid kampungku semakin memekik. Mengundang
jama’ah menyempurnakan kemenangan. Akupun segera beringsut perlahan kekamar
mandi kemudian berbondong-bondong pergi kemasjid. Hem, pagi yang sempurna. Tak
seorangpun tak pergi kemasjid. Dengan balutan pakaian terindah, aku menyambut
kemenangan ini.
Tradisi di kampungku, setelah
shalat idul fitri. Makan-makan bersama di masjid. Semakin memeriahkan suasanan
kemenangan. Aku tak sanggup lagi membayangkan betapa indah dan sempurnanya hari
ini. Berkesan.
Suasana haru nan bangga tercurah di
keluargaku. Keluarga sederhana yang jauh dari kemewahan. Namun, hari ini terasa
bahagia kurasa. Sumuannya berkumpul di rumah. ayuku yang sekolah di kota juga
pulang. Jarang sekali ayuk pulang, tapi saat ini ayuk ada diantaraku. Abangku
juga pulang,menambah lengkap suasana keluargaku. Damai.
Meski suasana ini hanya setahun
sekali. Tapi, aku merasakan keindahan ini benar-benar abadi. Kita jarang kumpul
lengakap seperti ini. Kadang ayuk pulang abang tak pulang, begitu sebaliknya.
Tapi jika lebaran tiba semuannya akan menjadi satu. Berbalut kebahagiaan di
antara kami; aku dan keluarga sederhanaku. Ini, hal yang begitu mengesankan.
benar-benar merasakan keutuhan cinta dari orang-orang yang kusayang dan arti
sebuah airmata terindah.
Suasana haru ini semakin
bertambah, tatkala aku dan keluargaku salin maaf-maafan. Dimulai dari kakak
tertuaku kemudian disusul adik-adiknya. Tak terasa perlahan arimata jatuh
membasahi seluruh pipi ini. Bibirku pun tertatih memohon maaf bapak, mamak,
ayuk, abang. Indahnya mengecup tangan beliau bagai tak ada bandingan di dunia
ini. Seberkas do’a dan maaf beliau semakin deras airmata ini mengalir.
Umurku 7 tahun, dan
disinilah aku mulai mengerti tentang kehidupan; Dimana aku mengerti arti sebuah
memaafkan. Hari ini, hari dimana aku bisa memaknai sebuah kemenangan. Kemenangan
yang sungguh didapat dari sebuah usaha. Senyumpun terlepas dariku. Maafanpun ku
lanjut ketetangga kampung. Bersama teman-temanku. Ah, tawa banggapun mengiringi
langkahku.
***
“ Allahu Akbar....Allahu
Akbar...Allahu Akbar...” Tertatih aku masih ikut melafalkan itu.
“ He, Nangis og.” Suara Gus
Shovi membuyarkan lamunanku. Gus Shovi putra abah di pondoku. Biasanya kalau
habis buka dia naik kekamar. Mau rokokan. Akupun buru-buru menghapus air mata.
Tak terasa rokok yang kusilipkan antara jari telunjuk-tengah membakar kulitku.
“ Mboten, sopo nangis.” Elakku pada
Gus Shovi.
“ La iku, kangen omah yo.” Desak
Gus Shovi memastikan. “ Sabar ya.” Lanjutnya.
“ Mboten biasa mawon Gus.” Masih
ku tutupi kesedihan ini. “ Niki Gus rokoknya.” Aku mengalihkan perhatiannya. Ya
malu lah, masak kelihatan sedih. Diambilnya sebatang kemudian turun lagi.
Mungkin Gus Shovi sengaja meninggalkanku. Aku faham sifatnya. Tak mau ikut
campur urusan orang. Paling ya ngledekin dikit.
: “ Ndik, engko nek takbiran
paranono aku nag kamar.” Teriak Gus Shovi dari arah tangga.
“ Siap bos.” Balasku teriak.
Kembali ku sulut rokok yang tingal
satu-satunya. Kuresapi bunyi takbir yang semakin berkumandang. Riuh alam
memuja, taluan beduk-beduk besar. Suara motor di jalan depan pondok semakin
meraung. Lantang tawa mulut-mulut menyabut kemenangan semakin membuat hatiku
pecah entah kemana. Aku rindu bapak, mamak, ayuk, abang dan keluarga-keluarga
kecil mereka. Melayangku antara Jawa-sumatra. Terasa dekat. Sedekat hatiku
dengan mereka.
Kamar ini semakin sunyi,
menyisakan aku, air mata dan sebatang rokokku. Sejak tadi hand phoneku
berbunyi, setiap detiknnya. Yah, jaman sekarang urusan minta maaf bisa
dilakukan dengan apa saja: telpon, SMS, atau apalah. Mengurai kata-kata yang
paling inidah. Berbincang semanis mungkin.
Namun, indahnya sungkem mengecup tangan. Berpelukan rindu
nan hangat. Takkan pernah bisa diwakili media apapun. Maafkan aku: bapak,
mamak, ayuk, abang. Ini lebaran kesekian kalinya tak sungkem pada kalian. Pelikku. (Mangun Kuncoro)
Jombang, Agustus/ Syawal 2012
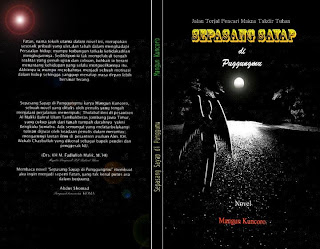
Komentar
Posting Komentar